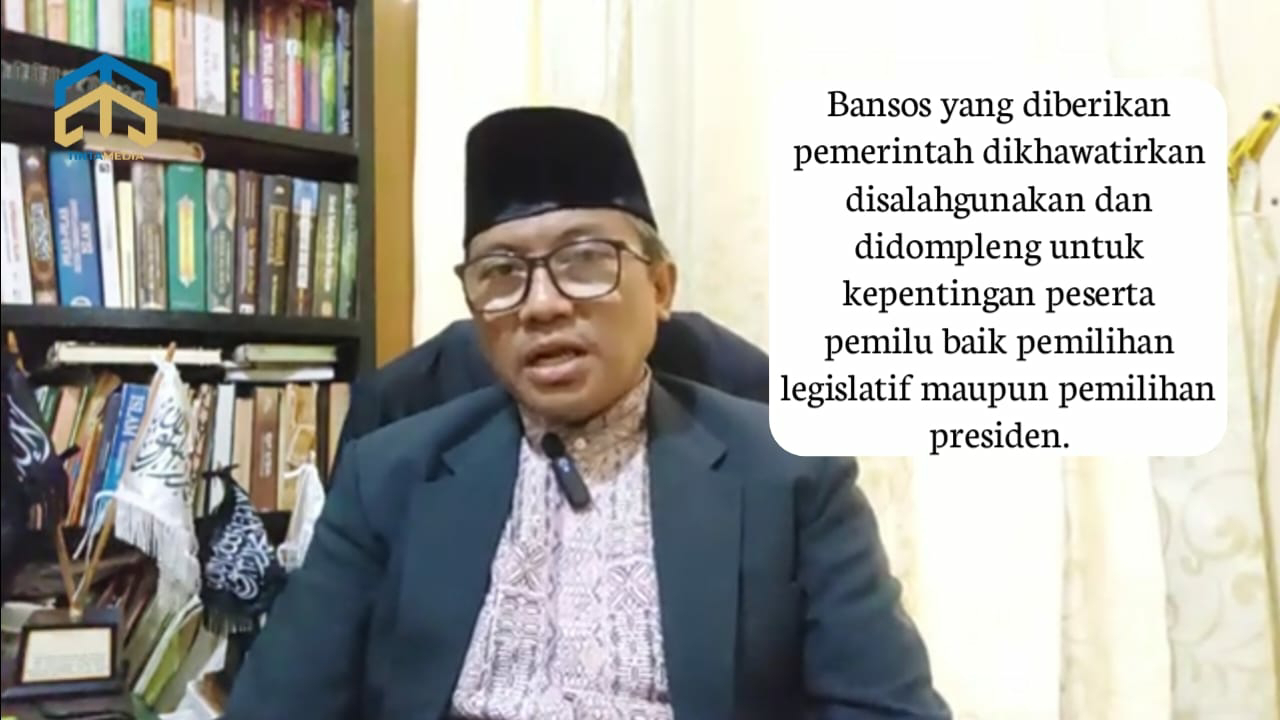Mekanisme Pemilu Jadi Masalah, Bukti Demokrasi Lemah
Tinta Media - Adanya kontestan pemilu di Pilkada Kabupaten Bandung yang masih menjabat kepemimpinan daerah (pejabat petahana) ada tiga orang, di antaranya adalah Dadang Supriatna selaku Bupati Bandung, Sahrul Gunawan selaku Wakil Bupati Bandung 2019-2024, serta Gun Gun Gunawan yang belum lama ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung 2024-2029.
Pemerhati kebijakan publik Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Direktur Jamparing Institute, Dadang Risdal Azis menyoroti tentang adanya perbedaan perlakuan regulasi petahana dan anggota legislatif yang menjadi kontestan di pilkada. Karena itu, perlu pendalaman komprehensif untuk menghindari dan meminimalisir konflik kepentingan.
Dadang mengatakan bahwa jika kontestan pilkada merupakan pejabat petahana, maka cukup mengajukan cuti kampanye, sedangkan jika pesertanya masih anggota DPRD, maka harus mengundurkan diri dari jabatan yang tertuang dalam UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU No.10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.
Dadang juga menyepakati soal adanya surat edaran menteri dalam negeri yang mengatur tentang pengunduran diri pejabat, Gubernur, dan Walikota pada pilkada 2024. Regulasi ini mengatur agar petahana yang akan mengikuti pilkada perlu mengundurkan diri. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan bagi anggota DPR, DPD, DPRD, serta PNS, TNI/POLRI, dan pegawai BUMN/BUMD, yang juga wajib mundur di pilkada jika menjadi kontestan di pilkada.
Pengaturan tentang hal tersebut menjadi masalah ketika ketetapan pemilu dilaksanakan secara berkala karena habisnya masa jabatan kepemimpinan, yaitu lima tahun. Oleh karena itu, harus ada UU dalam pengaturan pemilu, termasuk para kontestan yang sering kali diikuti oleh para pejabat yang masih berkuasa (petahana).
Realitas ini sangat niscaya terjadi dalam sistem demokrasi-kapitalisme, yang memandang jabatan sebagai kondisi yang menguntungkan, baik dari sisi pengaruh, fasilitas yang serba mewah, ataupun tunjangan serta sarana-pra sarana yang akan didapat jika meraih jabatan tersebut.
Ini semua merupakan sesuatu yang amat menggiurkan, sehingga banyak yang berlomba-lomba mencalonkan diri untuk meraihnya. Apalagi pejabat yang masih menjabat, mereka ingin terus mempertahankan jabatan dengan segala macam cara untuk melanggengkan kekuasaan, bahkan berkeinginan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi, hingga rela mengorbankan apa pun demi jabatan tersebut. Selanjutnya, mereka ingin mencalonkan lagi dan lagi. Hal ini terjadi karena adanya peluang bagi siapa pun untuk mencalonkan diri, walaupun sekadar untuk memenuhi syahwat politik secara pribadi atau golongan.
Mungkinan saja petahana menggunakan fasilitas negara ketika mencalonkan karena posisinya masih tetap berkuasa. Ini bisa terjadi manakala politik dijadikan sebagai tujuan untuk melanggengkan kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawannya baik dengan cara memukul maupun merangkul untuk memenangkan persaingan dalam pilkada.
Regulasi yang ada tidak serta-merta dapat mencegah peluang untuk berbuat curang walaupun dengan memanfaatkan kekuasaan. Apalagi dalam demokrasi, sah-sah saja menghalalkan segala cara dalam politik untuk meraih kekuasaan, seperti menggunakan bebagai macam kekuatan tipu daya, manipulasi untuk mempertahankan kekuasaan, selama memiliki kekuatan modal dan kekuasaan (pengaruh), yaitu dukungan dari para pemilik modal (kapitalis).
Hegemoni kepentingan para pemilik modal (kapitalis) melalui pemilu sebagai metode demokrasi inilah yang menyuburkan politik uang, suap, kolusi, dan korupsi, semata untuk kepentingan para kapitalis, dalam menguasai kendali politik dan kekuasaan dengan membentuk jaringan oligarki yang mampu memengaruhi jalannya pemerintahan beserta segala kebijakannya. Inilah demokrasi yang meletakan kedaulatan di tangan rakyat. Pada realitasnya, demokrasi hanya menjadi sarana bancakan antara penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan para pengusaha.
Pemilu, termasuk pilkada menjadi pintu awal masuknya hegemoni para kapitalis ini, sehingga para penguasa ada dalam kendali pengusaha (kapitalis) dalam menjalankan pemerintahan. Sementara, kepentingan rakyat hanya menjadi alat yang dipakai dalam meloloskan kebijakan yang pro-kapitalis, tapi tidak pro-rakyat. Hal ini menumbuhsuburkan para pemimpin yang rakus akan kekuasaan yang didukung oleh para kapitalis. Selamanya rakyat akan menjadi korban, seperti saat ini.
Oleh karena itu, jika ingin terjadi perubahan di tengah masyarakat, yaitu tercipta kesejahteraan dalam berbagai bidang kehidupan, maka tidak bisa dilakukan dengan sekadar mengubah pemimpin melalui pemilu. Namun, yang utama adalah mengubah sistem kapitalisme sekularisme yang diterapkan di negeri ini menjadi sistem yang sahih dan paripurna, yaitu sistem Islam.
Paradigma kekuasaan dan kepemimpinan dalam Islam adalah semata-mata untuk melayani rakyat. Ini karena makna politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan umat (rakyat) yang dilakukan oleh seorang kepala negara (khalifah) melalui penerapan syariat Islam secara kaffah (keseluruhan).
Untuk menjamin keberlangsungan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada khalifah tersebut, Islam menetapkan tujuh syarat in'iqad (sah) seorang khalifah tersebut, yakni muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu.
Ketujuh syarat tersebut wajib dipenuhi oleh seorang khalifah agar memenuhi kelayakan sebagai seorang pemimpin yang amanah, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab itu bukan hanya kepada manusia (rakyat) yang dipimpin, tetapi juga kepada Allah Swt.
Seorang pemimpin wajib berhukum pada hukum Allah dalam mengatur urusan rakyat, sebab kedaulatan berada di tangan syara' (syariat). Keberadaan rakyat wajib menasihati penguasa agar tidak menyimpang dari syariat Islam, sehingga akan menutup kemungkinan terjadi tindakan pejabat yang menyimpang dari syariat.
Kalaupun terjadi penyimpangan, maka akan diadukan kepada Mahkamah Mazalim. Dialah yang akan memproses hal tersebut, hingga sampai pada keputusan, apakah khalifah bisa tetap melanjutkan kepemimpinannya ataukah di-impeachment (diberhentikan) akibat terbukti melakukan penyimpangan (zalim), yang berarti telah hilang salah satu syarat in'iqad-nya.
Jika khalifah diberhentikan, maka wajib segera dilakukan pemilihan khalifah yang baru. Syariat Islam menetapkan bahwa pemimpin tidak dibatasi masa jabatan, karena faktor yang dapat memberhentikannya sebagai pemimpin adalah ketika sudah tidak terpenuhinya lagi syarat in'iqad pada seorang khalifah meskiy hanya satu.
Oleh karena itu, pemilu untuk memilih pemimpin tidak menjadi hal yang dilakukan secara berkala. Yang menjadi masalah dalam hal kepemimpinan bukan karena ia mencalonkan lagi atau tidak, tetapi apakah memenuhi syarat in'iqad ataukah tidak.
Dalam Islam, kepemimpinan tidak sekadar mendudukkan seorang muslim di panggung kekuasaan. Yang utama adalah penerapan Islam kaffah di dalam negeri dan mendakwahkan Islam ke seluruh dunia, dalam rangka mengatur urusan urus rakyat (umat). Wallahu alam bis shawab.
Oleh: Elah Hayani
Sahabat Tinta Media